Hari HAM Sedunia: Otsus Gagal Wujudkan Keadilan untuk Orang Asli Papua

Penulis: Ketua Umum Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, Papua Tengah, Vinsent Oniyoma
Di peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember 2025, Dewan Adat Daerah (DAD) Mimika, Papua Tengah menilai implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan selama 24 tahun telah gagal memenuhi janji normatifnya untuk melindungi dan memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) di bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Ekososbud).
Hari HAM Sedunia seharusnya menjadi momentum refleksi, bagaimana martabat kemanusiaan terwujud, terutama di wilayah perifer seperti Papua. Namun, bagi kami di Mimika, refleksi ini hanya menambah luka. Selama 24 tahun, Otsus telah gagal. Gagal secara substantif. Kesimpulan tercermin dalam kajian yang dilakukan oleh DAD Mimika.
Kajian kualitatif DAD Mimika menyoroti sebuah paradoks yang menyakitkan: di satu sisi, ada kerangka hukum yang komprehensif, mulai dari Undang-Undang Otsus hingga Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Ekonomi OAP. Di sisi lain, realitas di lapangan justru menunjukkan peminggiran ekonomi, pelemahan struktur sosial-budaya, dan berlanjutnya siklus kekerasan.
Selama 24 tahun Otsus berjalan, hampir tidak ada warga suku Amungme dan Kamoro yang menjadi pemain utama atau benar-benar menikmati dana Otsus untuk peningkatan kapasitas, seperti pendidikan tinggi di luar negeri. Ini menunjukkan betapa dangkalnya pemberdayaan yang terjadi.
Kegagalan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari implementasi yang bersifat semu. Spirit Otsus untuk pemberdayaan OAP terkorbankan oleh logika kekuasaan dan kepentingan ekonomi ekstraktif yang didominasi oleh korporasi besar seperti PT Freeport Indonesia. Kehadiran perusahaan tersebut, yang seharusnya menjadi mitra pemberdayaan, justru sering kali menjadi sumber konflik dan pelanggaran HAM yang berkepanjangan.
Dari perspektif DAD Mimika, terdapat tiga kegagalan utama. Pertama, adanya “kekosongan hukum” di mana aturan yang ada tidak diimbangi dengan penegakan yang tegas. Kedua, konsep kedaulatan negara yang sering ditafsirkan secara sempit untuk menindas kedaulatan adat, sehingga melukai martabat OAP. Ketiga, dampak dari kegagalan ini sangat parah, mencakup marginalisasi ekonomi, degradasi sosial-budaya, dan krisis kepercayaan terhadap negara.
DAD Mimika menolak Otsus secara keseluruhan jika tuntutan evaluasi total tidak dipenuhi, menurut Oniyoma, adalah bukti betapa dalamnya krisis legitimasi ini. “Ini bukan retorika, melainkan refleksi dari kekecewaan akibat janji-janji yang tidak pernah terealisasi. Kami meminta negara tidak lagi memperlakukan kami sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai mitra yang setara.
Meskipun dalam kekecewaan, DAD Mimika menawarkan solusi strategis untuk mengatasi kebuntuan saat ini. Solusi ini mengandung tiga pilar utama:
Evaluasi total dan pengawasan partisipatif: melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan dana Otsus selama 24 tahun oleh tim independen yang melibatkan perwakilan masyarakat adat. Selain itu, membentuk tim pengawas yang beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat adat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Reposisi Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai Pelaku Utama: Mengubah paradigma di mana MHA bukan lagi objek, melainkan pemilik hak yang sah atas tanah dan sumber daya alam. Setiap kebijakan, terutama terkait pemanfaatan sumber daya alam, harus didasarkan pada prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dari MHA.
Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif: Memfokuskan penyelesaian konflik pada pemulihan hubungan yang rusak, pengakuan atas penderitaan korban, dan pencarian solusi bersama. Negara harus memfasilitasi dialog antara masyarakat adat dengan korporasi untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan dampak lingkungan secara adil.
Solusi ini adalah sebuah panggilan untuk membangun kembali relasi yang rusak dan menciptakan fondasi baru bagi pembangunan yang benar-benar berkelanjutan dan berpihak pada OAP. Mengabaikan suara kami berarti membiarkan luka di Timur Indonesia terus bernanah. Sebaliknya, meresponsnya dengan tindakan nyata berarti memulai sebuah perjalanan panjang menuju rekonsiliasi dan keadilan yang sesungguhnya.
Pernyataan ini menjadi seruan bagi seluruh pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga pelaku usaha, untuk merefleksikan kembali komitmen mereka terhadap HAM dan memastikan bahwa Orang Asli Papua di tanah leluhurnya benar-benar menjadi tuan di rumah sendiri.***
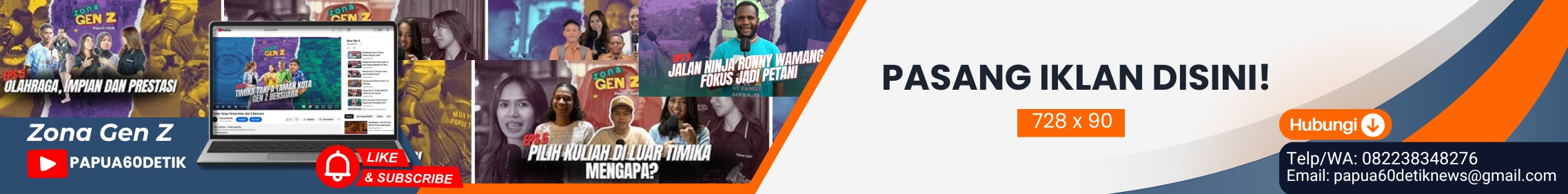
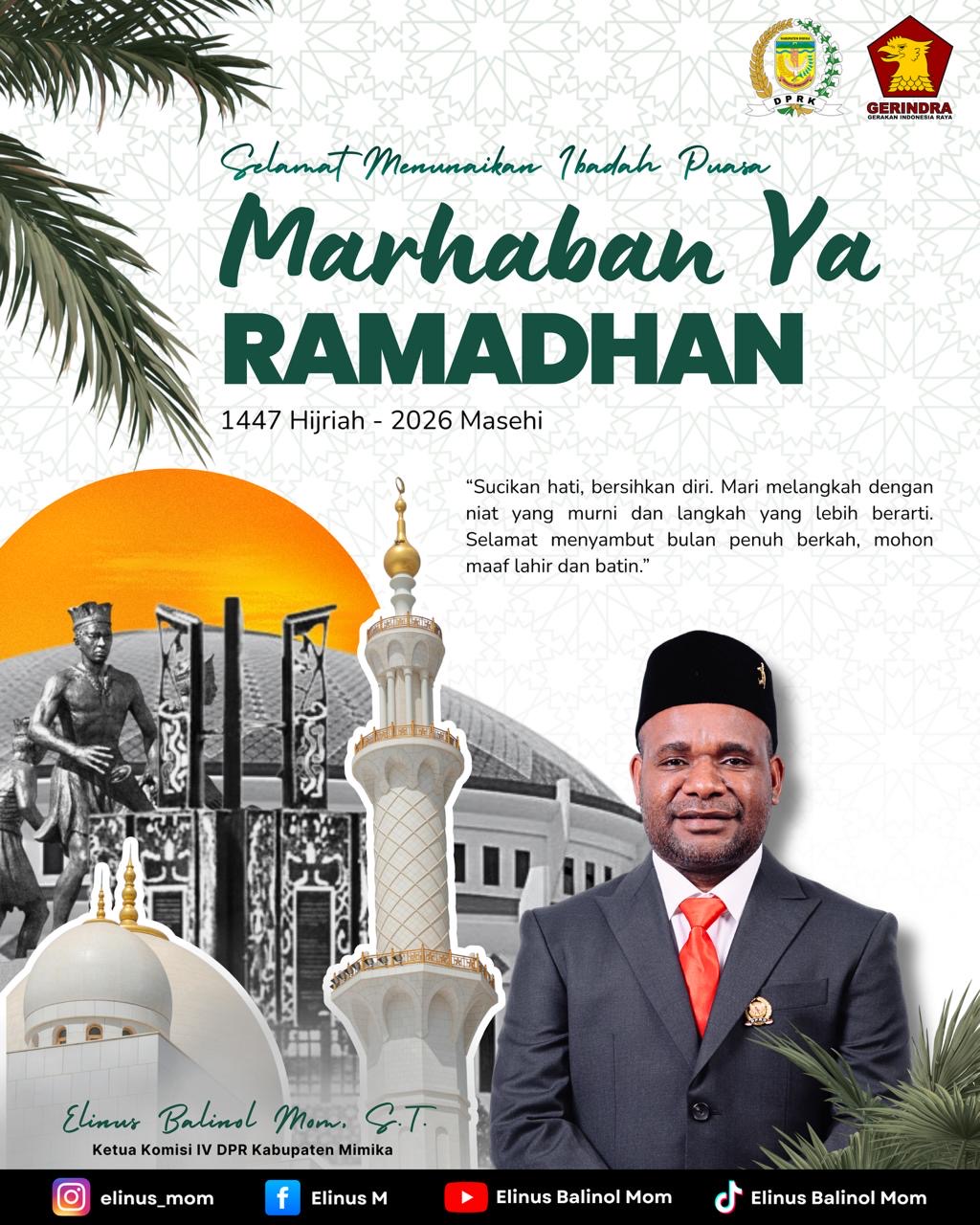
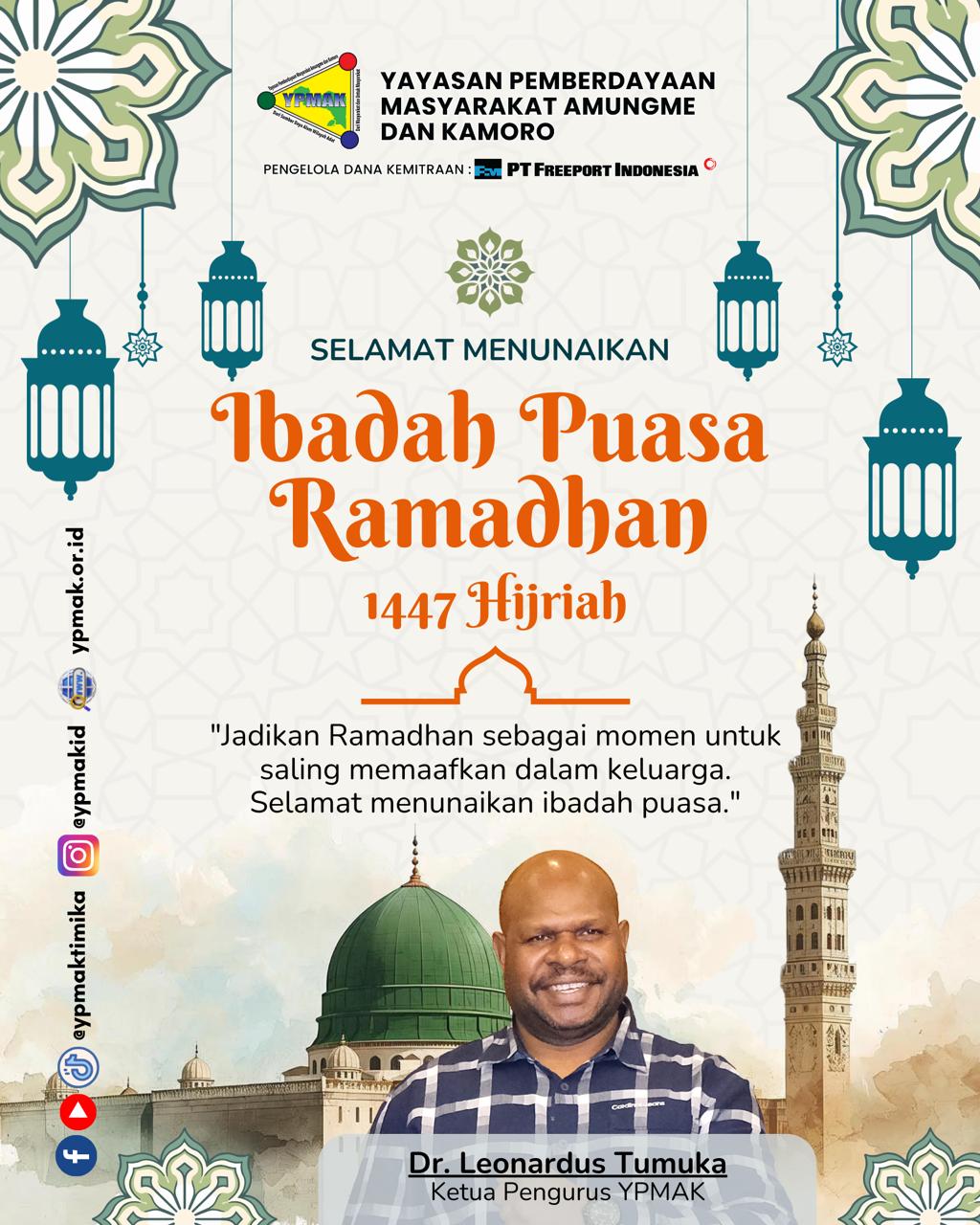





65865c894f2d3.jpg)




